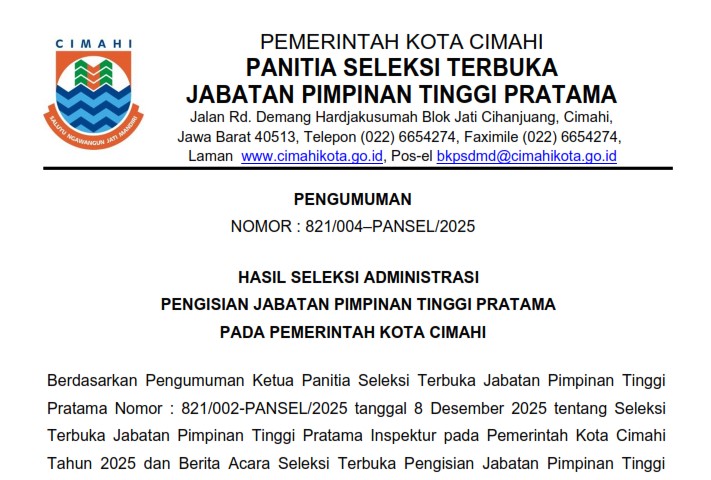- 24 Des 2025 • BKPSDMD Kota Cimahi Fasilitasi Wawancara Calon Kepala Disdukcapil Kota Cimahi Be...
- 24 Des 2025 • Dishub Kota Cimahi Siapkan Strategi Pengamanan Arus Lintas di Momentum Nataru
- 24 Des 2025 • Cimahi Ngibing Bakal Temani Libur Panjang Tahun ini di Pasar Awi
- 24 Des 2025 • Layanan Vaksinasi Hewan Gratis SiTerang Tuntas Digelar di Tahun 2025, Upaya Kota...
- 24 Des 2025 • UMKM Naik Kelas, Upaya Disdagkoperin Kota Cimahi Dorong UMKM Maju dan Sejahtera

Mengenal Kampung Adat Cireundeu

Cireundeu berasal dari nama “pohon reundeu”, karena sebelumnya di kampung ini banyak sekali populasi pohon reundeu. Pohon reundeu itu sendiri ialah pohon untuk bahan obat herbal. Maka dari itu kampung ini di sebut Kampung Cireundeu. Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, yang sebagia besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung Adat Cireundeu sendiri memiliki luas 64 ha terdiri dari 60 ha untuk pertanian dan 4 ha untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Masyarakat adat Cireundeu sangat memegang teguh kepercayaannya, kebudayaan serta adat istiadat mereka. Mereka memiliki prinsip “Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman” arti kata dari “Ngindung Ka Waktu” ialah kita sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri dan keyakinan masing-masing. Sedangkan “Mibapa Ka Jaman” memiliki arti masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak melawan akan perubahan zaman akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa hand phone, dan penerangan. Masyarakat ini punya konsep kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu, yaitu suatu daerah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
Leuweung Larangan (hutan terlarang) yaitu hutan yang tidak boleh ditebang pepohonannya karena bertujuan sebagai penyimpanan air untuk masyarakat adat Cireundeu khususnya.
Leuweung Tutupan (hutan reboisasi) yaitu hutan yang digunakan untuk reboisasi, hutan tersebut dapat dipergunakan pepohonannya namun masyarakat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Luasnya mencapai 2 hingga 3 hektar.
Leuweung Baladahan (hutan pertanian) yaitu hutan yang dapat digunakan untuk berkebun masyarakat adat Cireundeu. Biasanya ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkong atau ketela, dan umbi-umbian.
“Teu Boga Sawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat.”
“Tidak Punya Sawah Asal Punya Beras, Tidak Punya Beras Asal Dapat Menanak Nasi, Tidak Punya Nasi Asal Makan, Tidak Makan Asal Kuat.”

Empat kalimat tersebut seolah merangkum sejarah konsumsi rasi alias beras singkong di Desa Cireundeu. Hal tersebut berkaitan pula dengan tradisi nenek moyang mereka yang kerap berpuasa mengonsumsi beras selama waktu tertentu.
Tujuan puasa tersebut adalah mendapat kemerdekaan lahir batin. Ritual yang juga sekaligus menguji keimanan seseorang dan pengingat akan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa.
Pengolahan singkong menjadi rasi telah dilakukan masyarakat Kampung Adat Cireundeu selama kurang lebih 85 tahun. Hal tersebut membuat mereka mandiri soal pangan. Kehidupan di sini bisa dibilang tak terpengaruh gejolak ekonomi-sosial, terutama soal fluktuasi harga beras.
Begitu sampai di gerbang masuk Kampung Adat Cireundeu, kita akan disambut oleh monumen Meriam Sapu Jagat. Simbol Satria Pengawal Bumi Parahyangan ini juga dilengkapi tugu mungil bertuliskan Wangsit Siliwangi, yaitu jujur, ksatria, membela rakyat kecil, sayang pada sesama, dan menjadi wibawa.

Monumen meriam Sapu Jagat
Melewati Monumen Sapu Jagat kita masuk Gerbang Kampung Adat Cireundeu, setelah 20 meter memasuki kawasan kampung Adat Cireundeu kita akan menemukan Saung Baraya dan Bale Saresehan. Bale-bale ini biasa digunakan warga sekitar sebagai tempat pertemuan dan pagelaran seni. Bangunan dengan material bambu dan kayu ini memiliki luas sekitar 200 meter persegi
Setiap bulan Sura, bale-bale ini bakal digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang golek. Tradisi ini merupakan bentuk syukur pada Sang Maha Pencipta, atas semua kenikmatan yang sudah diterima.
Kampung Cirendeu dihuni oleh 367 kepala keluarga atau kurang lebih 1.200 jiwa. Terdiri dari 550 orang perempuan dan 650 orang laki-laki. Kondisi sosial masyarakat di kampung Cireundeu memiliki keadaan sosial yang terbuka dengan masyarakat luar. Namun kebanyakan masyarakat kampung Cireundeu tidak suka merantau atau berpisah dengan orang-orang sekerabat.
Pola pemukiman di kampung Cireundeu memiliki pintu samping yang harus menghadap ke arah timur. Bertujuan agar masuknya cahaya matahari ke bumi. Kehidupan antar masyarakat hidup dengan semangat gotong royong. Kampung Cireundeu didominasi masyarakat Muslim, namun keberadaan masyarakat adat menjadikan kampung banyak dikunjungi dan dijadikan tempat wisata, penelitian, acara adat, bahkan acara-acara lain yang bekerjasama dengan berbagai pihak.
Masyarakat adat tersebar di tiga RT. Jumlahnya sebanyak 67 kepala keluarga dengan 59 kepala keluarga. Berdiri sebuah masjid, dan bale sarasehan atau tempat untuk berkumpul atau pertemuan masyarakat adat.
Kehidupan yang harmonis dan saling gotong royong tergambar dalam setiap kegiatan seperti saat kelahiran yang saling membantu dalam menyediakan kendaraan. Saat ada keluarga warga yang meninggal, mereka saling membantu menggali tanah. Namun masyarakat yang berbeda keyakinan tak ikut serta dalam ritual pemakaman.
Sedangkan dalam perkawinan, masyarakat adat dan agama atau kepercayaan lain saling mengucapkan permisi dan mengundang satu sama lain. Namun kebiasaan masyarakat datang sehari sebelum acara perkawinan digelar. Sehingga saat hari perkawinan, undangan yang datang adalah keluarga, saudara, teman dan lainnya.
Adapun peringatan atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat, seperti peringatan satu sura atau tanggal 1 sura sesuai kalender Saka Sunda. Masyarakat dengan kepercayaan lain mengikuti persiapan dan ikut berpartisipasi dalam jalannya acara.
Masyarakat kampung Cireundeu memiliki kesenian gondang, karinding, serta angklung buncis yang biasanya ditampilkan dalam ritual upacara adat tertentu. Seperti upacara satu sura atau sekedar upacara menyambut tamu. Masyarakat adat di kampung ini adalah bagian dari Sunda Wiwitan yang tersebar di daerah Cigugur-Kuningan-Cirebon dengan nama Agama Djawa-Sunda (ADS), Sunda Wiwitan Suku Baduy di Kanekes (Lebak,Banten), Kasepuhan di Cipta gelar (Banten Kidul, Sukabumi), Cisolok-Sukabumi, Kampung Naga-Tasikmalaya.
Sunda Wiwitan berasal dari kata sunda dan wiwitan. dapat diartikan bahwa Sunda Wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda asli atau disebut juga agama Jati Sunda. Ia diyakini sebagai sebuah agama yang besar. Agama leluhur bangsa yang sangat peduli terhadap alam dan sopan santun. Adapun pandangan masyarakat adat Cireundeu terhadap agama adalah ageman (pegangan) untuk tuntunan hidup (keselamatan) yang tidak bisa lepas dari pemaknaan budaya yang artinya ketika seseorang beragama maka secara tidak langsung dan tidak disadari ia sedang menjalankan dan memaknai budaya yang melekat pada agama yang dianut.
Hal ini dikuatkan dengan adanya pepatah Sunda yang mengatakan bahwa “ulah poho kana kulah getih sorangan” yang artinya jangan lupa akan tanah kelahiran atau ibu pertiwi, serta sebuah ungkapan yang mengingatkan sebuah hak dan bukan “budaya batur dimumule, budaya sorangan dipohokeun cul dogdog tinggal igel” yang artinya budaya bangsa lain dipelihara, sementara budaya bangsa sendiri dilupakan. Konsep agama dalam kepercayaan masyarakat adat Cireundeu penganut Sunda wiwitan yakni Tuhan yang disebut “Gusti Sikang Sakang Sawiji Wiji” atau di atas segalanya pencipta mereka, setiap manusia akan kembali kepada Tuhan “Mulih Kajati Mulang Ka Asal”.
Pada abad 18 sesepuh Cirendeu atau mamak Haji Ali mempunyai kesadaran untuk tidak terjajah, kemudian mencari sebuah jawaban atau dukungan hingga ia mengembara dan pada abad 19 sampai di Cigugur Kuningan dan bertemu dengan Pangeran Madrais. Setelah bertemui dengan Pangeran Madrais, sesepuh Cirendeu merasa telah menemukan jawaban dan bertemu dengan orang yang dicari.
Pada abad yang sama, keturunan sesepuh Cireundeu menimba ilmu ke pangeran Madrais hingga cucu perempuan sesepuhnya yang bernama Ibu Anom atau Ibu Enceu menikah dengan Pangeran Madrais. Kemudian sekitar tahun 1930, Pangeran Madrais pernah mengunjungi Cireundeu. Pangeran Sepuh pernah mendengar keinginan warga Cireundeu yang menimba ilmu kepadanya untuk dapat merdeka lahir batin atau dalam arti untuk tidak mengkonsumsi nasi beras dari padi.
Hingga kini, masyarakat adat mengonsumsi singkong atau ketela yang disebut dengan rasi sebagai makanan pokok secara turun temurun. Diawali pada tahun 1918 ketika sawah-sawah yang mengering. Kemudian para leluhur menyarankan dan berpesan untuk menanamkan ketela sebagai pengganti padi. Karena tanaman ketela dapat ditanam pada musim kering maupun musim hujan dan melihat ketersediaan lahan untuk menanam padi semakin sempit dan kecil, banyak sawah-sawah yang telah berganti gedung.
Sejak 1924 masyarakat adat Cireundeu mulai mengonsumsi ketela hingga saat ini. Masyarakat adat mengolah singkong dengan cara digiling, diendapkan dan disaring menjadi aci atau sagu. Ampas dari olahan sagu yang dikeringkan juga dibuat menjadi rasi atau beras singkong. Tidak hanya itu, singkongpun diolah menjadi berbagai camilan seperti opak, egg roll, cireng, simping, bolu, bahkan dendeng kulit singkong yang dikemas dan dijual sebagai oleh-oleh.
Dengan konsistensi masyarakat adat yang mengonsumsi rasi sebagai makanan pokok, membuat masyarakat adat tidak pernah mengonsumsi beras. Hal ini bukan berarti masyarakat adat mengharamkan beras dari padi, namun melestarikan dan mengikuti pesan sesepuh. Rasa kenyang dari konsumsi ketela lebih lama dibandingkan dengan padi. Sehingga masyarakat adat cukup makan dua kali sehari.Berita Terkini



Artikel Populer



Pengumuman